- Transisi energi di Indonesia yang mengandalkan biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE) bertujuan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui FOLU Net Sink 2030, tetapi pelaksanaannya telah menyebabkan deforestasi, konflik lahan, dan ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Pengembangan HTE seringkali tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan banyak bergantung pada ekspor biomassa.
- Meskipun HTE seharusnya menjadi solusi energi terbarukan, sebagian besar biomassa justru berasal dari pembukaan hutan alam, bukan dari rehabilitasi atau perkebunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, sebagian besar hasil biomassa ini diekspor, mengurangi manfaat domestik.
- Transisi energi berbasis biomassa di Indonesia lebih berorientasi pada pasar ekspor, seperti yang terjadi di Gorontalo yang menyumbang 80,4% dari ekspor pelet kayu
Indonesia, senilai USD 11,2 juta. Sementara itu, target pengembangan HTE sering tidak tercapai, dengan banyak lahan yang dikonversi tanpa mengikuti prinsip keberlanjutan. - Meskipun HTE diharapkan menjadi solusi untuk energi terbarukan, banyak proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti di Jambi dan Gorontalo, dengan deforestasi yang mencapai ribuan hektare. Proyek HTE juga sering kali tidak disertai dengan perencanaan yang matang, seperti yang terlihat pada rendahnya tingkat
penanaman kembali dibandingkan dengan lahan yang digunduli. - Sebagian besar biomassa diperoleh melalui pembukaan lahan hutan alam, bukan dari rehabilitasi atau perkebunan yang sudah ada, yang menyebabkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan.
- Sebagian besar biomassa, terutama pelet kayu, diekspor ke luar negeri, dengan Gorontalo sebagai kontributor terbesar. Proses transshipment, yang melibatkan pengiriman tanpa dokumen legal yang memadai, turut menambah masalah pengawasan dan regulasi.
- Meski terdapat target FOLU Net Sink 2030 yang mengharuskan pembangunan 6 juta hektare hutan tanaman energi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak proyek HTE yang mempercepat deforestasi, bertentangan dengan upaya untuk meningkatkan penyerapan karbon.
- Pengembangan HTE sering kali mengabaikan hak-hak komunitas lokal, dengan janji kemitraan yang tidak terealisasi. Lahan-lahan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat untuk pertanian atau perkebunan sering kali diubah menjadi konsesi HTE tanpa kompensasi atau keuntungan yang jelas bagi mereka.
- Lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan mengarah pada eksploitasi hutan alam oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek HTE. Selain itu, banyak kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih luas.
- Dalam revisi dalam RUU EBET dan RUU KEN, kemungkinan akan dilakukan penurunan target bauran energi terbarukan yang sebelumnya ditetapkan 31% pada 2050, dikarenakan realisasi bauran energi Indonesia saat ini yang masih jauh dari harapan.

Indonesia telah mengajukan Enhanced NDC ke Sekretariat UNFCCC dengan target pengurangan emisi yang lebih tinggi, yakni sebesar 31,89 persen tanpa syarat (BAU) dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Enhanced NDC ini menjadi langkah awal menuju NDC Kedua Indonesia, yang akan diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050, dengan tujuan mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Target mitigasi ambisius sudah ditetapkan untuk sektor hutan, penggunaan lahan, dan energi, yang secara keseluruhan berkontribusi sekitar 97 persen dari komitmen nasional.
Pemerintah Indonesia berupaya menambah porsi energi terbarukan menjadi 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menekan emisi.
Namun, dampaknya terhadap sektor hutan dan lahan sangat besar. Pemerintah melalui KLHK menargetkan pembangunan Hutan Tanaman Energi oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri dengan luas 1,29 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan biomassa kayu.
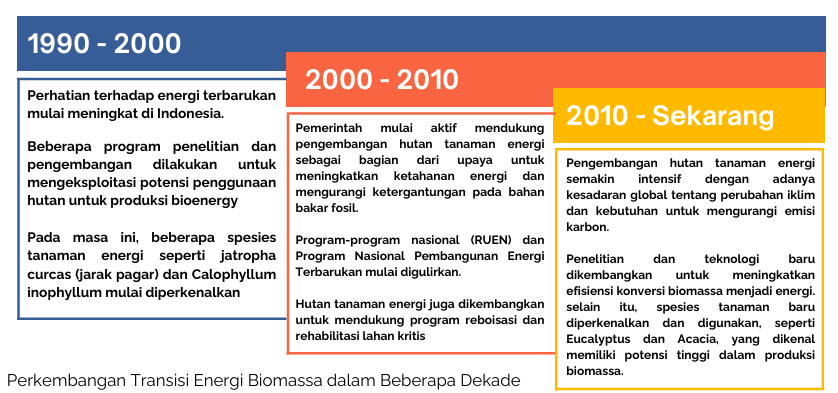
Di sisi lain, PLN dalam RUPTL juga berencana menggunakan biomassa kayu untuk co-firing bersama batu bara hingga 10 persen di 52 PLTU, dan hal ini diklaim sebagai energi bersih. Meski memiliki potensi besar, pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) di Indonesia juga membawa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah utamanya adalah risiko konflik penggunaan lahan, terutama jika lahan yang digunakan sudah menjadi area pertanian atau perkebunan masyarakat. Jika lokasi HTE dipilih secara kurang tepat, hal ini bisa menyebabkan penggusuran penduduk lokal dan memicu konflik agraria yang serius.
Pengelolaan yang tidak optimal juga bisa berdampak buruk pada lingkungan. Misalnya, praktik yang tidak ramah lingkungan seperti penebangan liar atau pembakaran hutan untuk membuka lahan baru dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem secara luas. Dampaknya akan terasa pada keanekaragaman hayati, serta kualitas air dan udara di sekitar area tersebut. Menurut laporan FWI (2023), pembangunan HTE telah menyebabkan hilangnya 55 ribu hektar hutan alam, sementara 420 ribu hektare hutan yang tersisa terancam dengan deforestasi terencana (planned deforestation).
Dari 31 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terlibat dalam pembangunan HTE, 8 izin perusahaan sudah dicabut dan 3 sedang dievaluasi. Skema multiusaha kehutanan sering menjadi dalih untuk memperluas penguasaan lahan oleh perusahaan.

Hasil investigasi tim FWI, perusahaan HTE memanen kayu alam untuk dijadikan bahan baku wood pellet, yang didapat bukan dari kayu hasil rehabilitasi atau tanam. Perusahaan melakukannya dengan cara tebang habis (land clearing). Sejalan dengan ini, dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, yang merupakan target NDC, mencatat bahwa untuk mencapai target net sink 2030 diperlukan pembangunan hutan tanaman, termasuk HTE, hingga 6 juta hektare. Dari angka ini, 2 juta hektare diharapkan dipenuhi melalui pemanfaatan hutan produksi (PBPH-HT) dan izin baru (Perhutanan Sosial), sementara sisanya akan dipenuhi melalui skema multiusaha kehutanan, kemitraan kehutanan, dan kerjasama Perhutanan Sosial. Dalam konteks ini, pembangunan HTE membutuhkan perhatian serius terkait implikasi kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal.
Saat ini ada 13 provinsi yang mengimplementasikan HTE, tiga diantaranya adalah Jambi, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.



