Tulisan ini adalah pengalaman dan keluh-kesah tentang betapa sulitnya menerobos dinding tebal yang menutup akses informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Berawal dari banyaknya keluh-kesah masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah-wilayah yang masih memiliki hamparan hutan dan lahan yang amat luas. Tersebar di seluruh pelosok Negeri ini, termasuk di Pulau Jawa, walaupun terkenal dengan populasi penduduk yang amat padat.
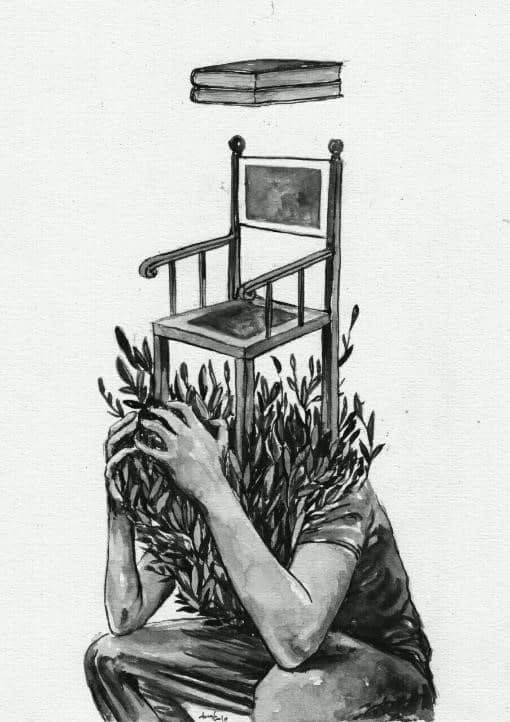
Sering muncul pernyataan dari masyarakat, “tanah ini punya jendral a, jenderal b, si c, si d”, “hutan ini punya pak C, Ibu E, Bapak P, anaknya Pak J, Menantunya Pak B”. dan masih banyak nama-nama besar lainnya di negeri ini yang sering disebutkan sebagai penguasa tanah. Namun, apakah itu benar? Atau hanya “asal sebut” dari sebagian besar masyarakat di Indonesia? Jika itu hanya pernyataan spontan dari masyarakat, mengapa hampir di setiap daerah peryataan ini selalu muncul?
Kerap kali hal seperti ini dianalogikan sebagai “rahasia umum” yang sangat amat sulit mencari pembuktiannya. Apakah nama-nama besar yang sering terdengar itu benar adanya menguasai hutan dan lahan di Indonesia? Atau hanya orang-orang tertentu yang sengaja menggunakan nama-nama besar di negeri ini sebagai “tameng” untuk mengamankan usaha mereka?.
Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak akan bisa dijawab tanpa adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan hutan dan lahan. Jika informasi-informasi seperti itu tidaklah dibuka, janganlah menyalahkan masyarakat yang terus berspekulasi dan berimajinasi tenang “gurita-gurita” besar yang menguasai negeri ini.
Lalu pertanyaannya, dimana informasi-informasi seperti itu tersedia? Bagaimana caranya agar informasi-informasi seperti di atas dapat diketahui oleh publik?
UUD 45 pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Celakanya, banyak kebijakan-kebijakan yang hanya menggunakan pasal ini sebagai alat kekuasaan, tidak melihat pasal-pasal dan ayat-ayat lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Seharusnya, penguasaan disini bukan lantas memiliki, namun sebagai kontrol yang mampu menjamin keadilan, menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan juga menjaga lingkungan.
Dalam pengelolaannya, secara garis besar tanah di negeri ini dibagi menjadi dua status, Kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Secara penguasaan “gurita” izin pemanfaatan, di dalam kawasan hutan biasa dikenal dengan adanya HPH, HTI, dan juga pertambangan. Sedangkan di luar kawasan hutan, biasa dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU). Salah satu bentuk usaha di HGU yang saat ini merajarela di Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit yang selalu digadang-gadang sebagai penghasil devisa terbesar.
Dalam pengelolaannya, pemerintah “mengontrakan” tanah kepada pengusaha-pengusaha dalam jangka waktu tertentu. Untuk kasus HGU, tenggang waktunya sampai 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Celakanya, perjanjian “kontrak-mengontrak” tersebut tidak pernah melihat apakah ada manusia yang sudah lebih dahulu memanfaatkan hutan ataupun lahan tersebut. UUD 45 pasal 33 ayat 2 tersebut justru ditafsirkan tanpa melihat pasal-pasal lainnya sehingga muncullah kesewenangan dengan claim “tanah milik negara”. Tidak heran, jika konflik agraria di negeri ini tidan pernah terselesaikan bahkan jumlah dan korbannya semakin bertambah banyak.
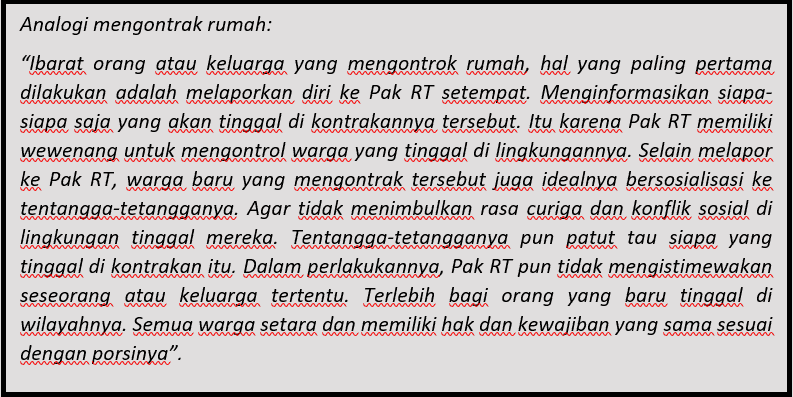
Seperti halnya analogi di atas, Negara yang dianalogikan sebagai Pak RT hanyalah alat kontrol, sementara sang pemilik rumah adalah orang yang berbeda. begitu juga dengan izin-izin HGU yang dikeluarkan, izin HGU tidak dapat dikeluarkan semena-mena, harus melihat terlebih dahulu masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut. terlebih masyarakat yang secara turun temurun telah menguasai dan mengelola hutan dan lahan yang ada di lingkungan mereka.
Tentunya pemberian izin HGU tidak cukup dengan hanya sekedar melihat ada atau tidaknya masyarakat yang mendiami areal itu. Masyarakat berhak tau siapa orang yang meliki izin HGU itu, sampai dimana batasnya, untuk apa peruntukannya, dan sampai kapan dia “mengontrak”. Begitu juga dengan pemilik izin HGU, dia harus pro aktif bersosialisasi dengan masyarakat, agar apa yang yang dilakukan di wilayah yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dapat terkontrol. Sehingga sudah sewajarnya pengelolaan lahan-lahan HGU dilakukan secara terbuka dan transparan.
Sejak bulan September tahun 2015, FWI mencoba mengajukan permohonan informasi data HGU ke kementerian ATR/BPN. Namun satu bulan lebih permohonan informasi tersebut diacuhkan, KemenATR/BPN sama sekali tidak menanggapi surat permhohonan informasi yang diberikan. Lantas, FWI mengajukan surat keberatan karena diacuhkannya permohonan informasi itu. Surat keberatanpun tetap diacuhkan sampai pada akhirnya di Desember 2015 sengketa informasi data HGU didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
Sejak sengketa informasi HGU dilayangkan ke KIP, proses sengketa informasi di KIP yang memakan waktu selama 7 bulan tersebut menghasilkan 9 kali proses sidang dan 1 kali mediasi. Dari ke-10 proses itu, ada 3 proses pihak ATR/BPN mengacuhkan dengan tidak hadir tanpa alasan. Tepatnya pada 22 Februari 2016 sidang pemeriksaan awal ke-2, 27 April 2016 pada proses mediasi, dan 13 Mei 2016 pada sidang ajudikasi. Hingga akhirnya pada 22 Juli 2016 KIP memutuskan data HGU merupakan informasi publik yang harus tersedia setiap saat.
Pasca putusan Komisi Informasi, KemenATR/BPN belum juga mau membuka informasi HGU. Bahkan bulan berikutnya tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2016 ATR/BPN mengajukan banding ke PTUN atas putusan KIP ini. Namun lucunya, tepat pada hari persidangan pertama (16 November 2016) di PTUN, pihak ATR/BPN pun tidak hadir dalam proses persidangan.
Terpaksa proses persidangan tetap berlanjut tanpa dihadiri pihak yang mengajukan. Setelah menjalani 7 kali persidangan di PTUN, pada Desember 2016 putusan PTUN justru semakin menguatkan putusan KIP yang menyatakan dokumen HGU merupakan informasi publik.
Lagi-lagi, ATR/PBN pun tidak menerima putusan PTUN yang semakin menguatkan putusan KI-Pusat. Mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah agung (MA) satu bulan kemudian pada tanggal 6 Februari 2017. Puncaknya, pada 6 Maret 2017 MA pun menolak kasasi yang diajukan oleh ATR/BPN dan justru semakin menguatkan putusan PTUN.
Hampir tiga tahun terhitung sejak putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa dokumen HGU adalah dokumen terbuka, kementerian ATR/BPN tidak juga mau membuka informasi HGU. Janji-janji untuk membuka data HGU pun sudah sering kali terdengar dan menjadi hiasan penghibur di berbagai macam media. Termasuk juga menghibur lebih dari 53 ribu orang yang telah menandatangani petisi online agar kemenATR/BPN menjalankan putusan MA dengan membuka data HGU.
Disamping menghibur masyarakat yang menuntut adanya keterbukaan informasi dokumen HGU, para pejabat di negeri ini juga membangun wacana dengan membangun argumentasi-argumentasi yang menyatakan bahwa dokumen HGU bukanlah dokumen publik. Walaupun, argumentasi-argumentasi yang diucapkan sebenarnya sudah dimentahkan dengan adanya putusan pengadilan bahkan sampai ke MA. Artinya ada wacana lain yang dibangun tanpa memperhatikan putusan pengadilan. Dalam arti lain, putusan pengadilan telah dilecehkan oleh pejabat-pejabat publik yang tidak mau membuka informasi HGU.

Setelah argumentasi-argumentasi yang tidak pernah mempertimbangkan putusan pengadilan bermunculan dari para pejabat publik, pada Oktober 2019, Kementerian ATR mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke PTUN atas polemik data HGU. Ini memperlihatkan adanya intervensi yang cukup kuat dari “gurita-gurita” yang tidak terlihat untuk tidak membuka data HGU.
Langkah ini semakin memperlihatkan ketidakprofesionalan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan perkara sengketa HGU ini. Dimana sebelumnya pasca putusan MA, KemenATR/BPN berjanji akan memberikan informasi HGU dan meminta FWI untuk menunggu penyelesaian mekanisme penyerahan dokumen yang sedang disusun dan ditempuh melalui Ombudsman RI.
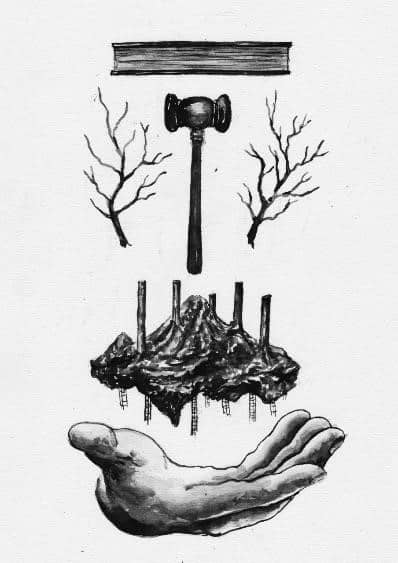 Alih-alih menunggu mekanisme penyerahan dokumen, yang didapat FWI justru surat panggilan sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak ATR/BPN. Tertulis sidang PK akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019, dengan agenda pengambilan sumpah. Lucunya lagi, Kementerian ATR/BPN lagi-lagi tidak hadir di persidangan, sehingga sidang pun ditunda di minggu depannya.
Alih-alih menunggu mekanisme penyerahan dokumen, yang didapat FWI justru surat panggilan sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak ATR/BPN. Tertulis sidang PK akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019, dengan agenda pengambilan sumpah. Lucunya lagi, Kementerian ATR/BPN lagi-lagi tidak hadir di persidangan, sehingga sidang pun ditunda di minggu depannya.
Cerita singkat ini, memperlihatkan ironi yang terjadi di Indonesia. Disaat pemerintah terus bersuara “ini negara hukum” dan mendorong masyarakat mematuhi hukum dan tidak main hakim sendiri, justru perangkat negara lah yang tidak patuh dengan hukum. Jadi jangan heran jika hukum di Negeri ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan jangan juga heran jika banyak masyarakat yang tidak patuh dengan hukum jika perangkat negara sendiri memberi contoh untuk melawan hukum.
Pada kasus HGU ini, sebenarnya ada opsi lain untuk melaporkan Kementerian ATR/BPN dan para pejabat lainnya ke ranah kepolisian karena tindakannya yang melawan hukum. Namun, pertanyaan untuk kita semua, jika itu dilakukan apakah pemerintah dapat menjamin hukum di negeri ini dapat ditegakkan dengan adil…. ?
–Sekian–
Mufti F. Barri




2 Comments
riama simamora
Negara yg membuat Hukum tapi Negara sendiri juga yg melanggar hukum
Pay Pardi
seperti itulah,,temuan dari pembuat aturan