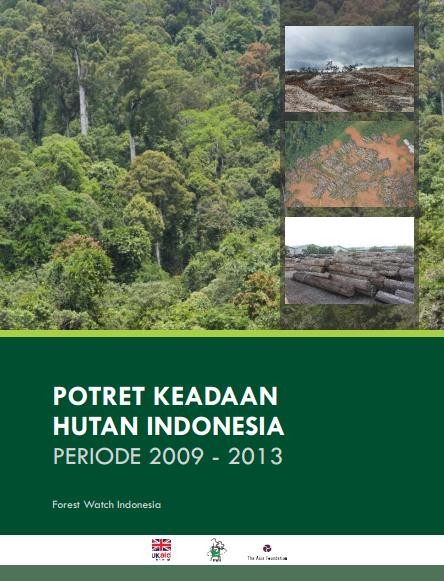Indonesia menempati peringkat ke-14 negara-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan.
Kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2009) juga memprediksi bahwa Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia masih akan terus meningkat dari 1,72 Gton CO2e pada tahun 2000 menjadi 2,95 Gton CO2e pada tahun 2020.
Menghadapi sorotan dunia terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2010-2020. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pitsburg untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia sebesar 26-41 persen. Dalam rencana aksi tersebut disebutkan bahwa 88 persen dari total emisi GRK yang ingin diturunkan oleh pemerintah berasal dari sektor kehutanan.
Perkiraan mengenai peningkatan emisi gas rumah kaca bisa dipahami bila merujuk pada kecenderungan deforestasi yang masih tinggi. Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 1996-2000 laju deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta hektare per tahun (FWI & GFW, 2001). Pada rentang 10 tahun berikutnya, laju deforestasi mencapai 1,5 juta hektare per tahun (FWI, 2011), dan Potret Keadaan Hutan Periode 2009-2013 ini menemukan laju deforestasi sebesar 1,1 juta hectare per tahun (FWI, 2014).
Laju deforestasi yang cenderung tinggi adalah dampak dari tata kelola kehutanan yang tak kunjung membaik (FWI, 2014). Empat penyebab tidak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah: (a) perencanaan tata ruang yang tidak efektif, (b) masalah-masalah terkait dengan tenurial, (c) pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, dan (d) penegakan hukum yang lemah serta maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan (UNDP, 2013). Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2001 disebutkan bahwa tingginya tingkat deforestasi disebabkan oleh kebijakan pemerintah terutama kebijakan produks kayu nasional.
Di sisi lain, tingkat deforestasi yang masih tetap tinggi adalah karena sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.4 Hal senada dipaparkan melalui hasil analisis Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2010. Disebutkan dalam analisis tersebut bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sejalan antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dalam pengelolaan hutan di Indonesia.
Tata kelola kehutanan yang baik (good forest governance) dicirikan dengan adanya transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai, partisipasi masyarakat secara substansial dan signifikan mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan, akuntabilitas yang tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan, serta koordinasi para pihak yang berjalan efektif dan efisien dalam setiap pengambilan keputusan. Tata kelola kehutanan yang baik adalah pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (inklusif) dan transparan. Tata kelola kehutanan akan ikut menentukan berhasil atau tidaknya Upaya pemerintah dalam menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan.
Ketersediaan data dan informasi kehutanan yang akurat merupakan salah satu factor yang sangat penting sebagai bentuk pertanggung-gugatan pemerintah. Data dan informasi tidak hanya dibutuhkan oleh pemangku kebijakan untuk melaksanakan tahapan pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan secara benar tetapi juga sebagai penghubung bagi kepentingan masyarakat dalam fungsi kontrol dan pengawasan.
Pengelolaan hutan sebagai bagian dari Tata Kelola Hutan merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis dan berulang. Melalui proses ini maka setiap kebijakan pengelolaan berikut implementasinya harus selalu diberikan input-input apabila arah pengelolaan hutan menyimpang dari tujuan semula. Input dan evaluasi hanya akan diperoleh apabila ada keterpenuhan data dan informasi kehutanan yang akurat dan memadai untuk dilaksanakannya pemantauan secara terus menerus.