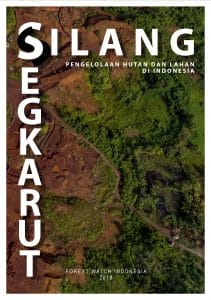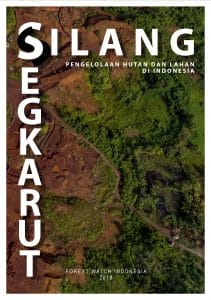 Pada tahun 1980-an laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 1 juta hektare/tahun, kemudian meningkat sekitar 1,7 juta hektare/tahun pada awal 1990-an, bahkan semakin meningkat pada 1996 menjadi 2 juta hektare/tahun. Meningkatnya laju deforestasi akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam, khususnya hutan Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI/GFW, 2001).
Pada tahun 1980-an laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 1 juta hektare/tahun, kemudian meningkat sekitar 1,7 juta hektare/tahun pada awal 1990-an, bahkan semakin meningkat pada 1996 menjadi 2 juta hektare/tahun. Meningkatnya laju deforestasi akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam, khususnya hutan Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI/GFW, 2001).
Kemudian di periode selanjutnya, laju deforestasi mengalami penurunan sekitar 1,5 juta hektare/tahun selama 2000-2009 (FWI, 2011) dan menjadi 1,1 juta hektare/tahun pada periode 2009-2013 (FWI, 2014). Penurunan laju deforestasi ini bukan karena prestasi pemerintah berhasil melindungi hutan, melainkan karena luas hutan Indonesia yang semakin menyusut.
Sampai 2015 seluas 19,6 juta hektare diberikan untuk 269 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 10,7 juta hektare untuk 280 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (KLHK, 2015). Sementara sampai 2017, seluas 12,27 juta hektare diberikan untuk 1412 perkebunan kelapa sawit (Dirjenbun, 2017) dan sebanyak 9433 Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perusahaan tambang (PWYP, 2017). Jumlah dan luasan izin-izin tersebut tentu tidak sebanding dengan hak pengelolaan hutan dan lahan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat.
Tidak hanya soal ketimpangan penguasaan, persoalan pengelolaan hutan yang buruk juga terlihat dari tumpang tindihnya antar perizinan dan klaim wilayah kelola masyarakat. Setidaknya ada 14,7 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan (FWI, 2014).
Kajian Forest Watch Indonesia (FWI) 2017 di delapan Provinsi tersebut menemukan pada periode 2013-2016 ada 8,9 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Bahkan ada 526,8 ribu hektare wilayah adat tumpang tindih juga dengan konsesi-konsesi tersebut.
Terdapat dua dampak yang terlihat jelas akibat tidak pernah terselesaikannya permasalahan tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan. Tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan berdampak pada deforestasi dan konflik sosial. Deforestasi akibat tumpang tindih pengelolaan terjadi akibat adanya izin-izin perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, izin-izin konsesi baik itu HPH, HTI, perkebunan, ataupun pertambangan yang berada di dalam wilayah moratorium juga berdampak pada hilangnya hutan alam di wilayah yang sebenarnya tidak diperbolehkan adanya izin pengelolaan.
Kondisi hutan di delapan Provinsi menunjukkan bahwa sampai tahun 2016 menyisakan 27,3 juta hektare atau 41 % dari luas daratan delapan Provinsi tersebut. Provinsi dengan luas hutan terbesar adalah Kalimantan Timur dengan luas sekitar 5,9 juta hektare, sedangkan Provinsi dengan luas hutan terkecil adalah Sumatera Selatan dengan luas 0,73 juta hektare.
Pada kurun waktu 2013-2016, berdasarkan analisis FWI menunjukkan adanya kehilangan hutan atau deforestasi seluas 1,8 juta hektare di delapan Provinsi. Perubahan tutupan hutan yang tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sekitar 472 ribu hektare, di ikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas sekitar 373 ribu hektare dan Kalimantan Barat yaitu sebesar 241 ribu hektare.
Kehilangan hutan alam atau deforestasi kerap terjadi akibat tumpang tindih antara kawasan hutan dan perkebunan. Begitu juga halnya tumpang tindih yang terjadi antara kawasan hutan dan pertambangan. Aktivitas-Aktivitas yang terdapat pada sektor perkebunan dan pertambangan sebagian besar dapat menghilangkan hutan alam dari area-area yang terjadi tumpang tindih tersebut.
Hasil analisis FWI di delapan Provinsi lokasi kajian menemukan terdapat 1,4 juta hektare kawasan hutan telah dibebani izin perkebunan kelapa sawit. Sekitar 61% lokasi tumpang tindih tersebut berada pada kawasan hutan dengan fungsi produksi (HP dan HPT). Dalam pengelolaan kawasan hutan, hutan produksi umumnya diperuntukan bagi IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Adanya izin perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi semakin memperlihatkan buruknya tata kelola hutan khususnya dalam sektor perizinan. Pada rentang waktu 2013-2016 area-area tumpang tindih tersebut telah kehilangan hutan alam lebih dari 50 ribu hektare, dan hanya menyisakan 424 ribu hektare atau 29% hutan alam dari area yang terjadi tumpang tindih.
Tumpang tindih antara kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit banyak terjadi di area kawasan hutan produksi. Begitu juga halnya dengan deforestasi yang terjadi pada area hutan produksi yang mencapai 27 ribu hektare. Sekitar 87% atau 568 ribu hektare izin perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan merupakan area hutan produksi yang telah dibebani izin IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Dimana Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang paling luas terjadi tumpang tindih antara perkebunan kelapa sawit dengan dua izin usaha bidang kehutanan tersebut. Selain itu, di 8 Provinsi lokasi kajian juga telah terjadi deforestasi pada rentang waktu 2013-2016 seluas lebih dari 24 ribu hektare pada area tumpang tindih perizinan di bidang kehutanan (HPH dan HTI) dan perkebunan kelapa sawit.
Luasan perkebunan kelapa sawit pada penelitian ini adalah data yang menggambarkan luasan izin perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Di lain sisi, tumpang tindih antara kawasan hutan dengan perkebunan kelapa sawit jauh lebih luas jika melihat kondisi faktual tutupan lahan di dalam kawasan hutan.
Selain dengan izin perkebunan kelapa sawit, juga terjadi tumpang tindih antara kawasan hutan dengan izin pertambangan. Bahkan dengan luasan tumpang tindih yang jauh lebih besar mencapai 8,6 juta hektare. Pada tahun 2016, di dalam wilayah tumpang tindih antara kawasan hutan dan izin pertambangan terdapat hutan alam seluas 4,4 juta hektare atau 51% dari total area yang tumpang tindih. Luas hutan alam tersebut telah berkurang seluas 551 ribu hektare jika dibandingan dengan tahun 2013. Adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan, diduga menjadi penyebab hilangnya hutan alam di dalam area yang tumpang tindih tersebut.
Sama halnya tumpang tindih yang terjadi dengan perkebunan, tumpang tindih antara kawasan hutan dengan pertambangan juga banyak terjadi di dalam kawasan hutan produksi. Dimana 52% atau lebih dari 4 juta hektare izin pertambangan terjadi di dalam area hutan produksi (HP dan HPT). Hal ini juga menimbulkan adanya potensi konflik yang lebih komplek. Konflik yang terjadi tidak hanya dengan masyarakat, namun juga dengan perusahaan di sektor kehutanan yang telah mendapatkan izin pengelolaan baik dalam bentuk IUPHHK-HA ataupun IUPHHK-HT.
Sama halnya tumpang tindih dengan perkebunan, lokasi terbesar tumpang tindih antara kawasan hutan dan pertambangan juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Area tumpang tindih di Provinsi tersebut telah menyumbang deforestasi lebih dari 144 ribu hektare pada tahun 2013-2016. Dari data-data yang disajikan, terlihat bahwa maraknya aktivitas pertambangan khususnya pertambangan batubara di Kalimantan Timur menjadi salah satu penyebab hilangnya hutan alam di Provinsi tersebut.
Selain tumpang tindih yang terjadi antar sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan, tumpang tindih juga terjadi pada ketiga sektor tersebut dengan kebijakan moratorium pada wilayah penundaan pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan moratorium tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden No. 6 tahun 2017. Kebijakan Moratorium, telah dimulai sejak tahun 2011 melalui Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011. Aturan ini merupakan perpanjangan penundaan sementara (moratorium) izin hutan dan lahan yang sudah berjalan enam tahun, dengan perpanjangan setiap dua tahun.
Sebagai dokumen non-legislatif, INPRES tidak memiliki konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan. Ditambah lagi dengan tidak dilibatkannya Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM dalam INPRES No. 10 Tahun 2011, INPRES No.6 Tahun 2013, dan INPRES No. 8 Tahun 2015. Ekspansi perkebunan dan tambang yang menggerogoti kawasan hutan seharusnya menjadi alasan untuk memasukkan kedua Kementerian tersebut sebagai pihak yang mendapat instruksi ini. INPRES No. 6 tahun 2017 memang telah memasukkan Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintah yang mendapat instruksi. Masih tidak dimasukkannya kementerian ESDM dalam instruksi tersebut membuat kebijakan moratorium saat ini tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan deforestasi di Indonesia.
Kajian yang dilakukan FWI pada tahun 2017 di delapan Provinsi terlihat bahwa sampai dengan tahun 2016 terdapat lebih dari 4,4 juta hektare wilayah moratorium yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, baik itu dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Perkebunan Kelapa Sawit, dan Pertambangan. Sekitar 45% dari luas tumpang tindih tersebut merupakan izin pertambangan, 38% perkebunan kelapa sawit, 12% IUPHHK-HA, dan 6% IUPHHK-HT. Adapun luas hutan alam tersisa pada area tumpang tindih adalah 2,1 juta hektare atau 47% dari luas area yang tumpang tindih dengan wilayah moratorium di delapan Provinsi tersebut.
Tumpang tindih kebijakan antara moratorium dan konsesi perkebunan dan pertambangan mencapai 82% dari total 4,4 juta hektare tumpang tindih yang terjadi. Sisanya terjadi antara wilayah moratorium dengan izin pengelolaan hutan berupa HPH dan HTI. Hal ini merupakan implikasi tidak dimasukkannya Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM sebagai lembaga negara yang diinstruksikan dalam 6 tahun pertama berjalannya INPRES moratorium. Adanya izin perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di dalam wilayah moratorium berdampak pada hilangnya 117 ribu hektare hutan alam di delapan Provinsi.
Tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan sudah menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai hingga saat ini. Tidak terselesaikannya permasalahan tumpang tindih pengelolaan ditenggarai juga menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia. Deforestasi akibat tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan umumnya terjadi akibat adanya kebijakan yang bersebrangan antara perlindungan hutan dan pemanfaatan hutan. Selain itu, tumpang tindih pengelolaan juga berakibat pada konflik pengelolaan sumberdaya alam yang berkepanjangan dan tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Baik itu konflik horizontal (masyarakat dengan masyarakat, perusahaan dengan perusanaan) ataupun vertikal (masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah). Dari banyaknya konflik akibat tumpang tindih yang terjadi, umumnya berdampak terhadap konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Penelitian FWI menunjukan bahwa 3,35 juta hektare atau 83 persen wilayah adat berada dalam kawasan hutan. Lahirnya UU Kehutanan tahun 1999 yang hanya membagi hutan menjadi satu bentuk yakni hutan Negara membuat masyarakat adat sangat terbatas dalam mengakses sumberdaya alam yang berada di wilayah adatnya sendiri.
Data FWI menunjukan wilayah adat di delapan Provinsi yang paling besar berada dalam hutan lindung dan kawasan konservasi yaitu sebesar 2 juta hektare atau 50% dari luas wilayah adat yang sudah dipetakan. Melihat hal ini, 2 juta hektare tersebut berpotensi mengalami pemindahan karena berada di dalam hutan lindung dan kawasan konservasi.
Selain tumpang tindih dengan dengan kawasan hutan, tumpang tindih yang rumit juga ditemukan antara wilayah adat dengan konsesi kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Sebanyak 38 persen wilayah adat yang sudah terpetakan tumpang tindih dengan konsesi. Hasil analisis FWI menunjukan hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih lahan antara wilayah adat dengan perusahaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, perkebunan dan pertambangan sekitar 1,5 juta hektare. Yang tertinggi adalah tumpang tindih dengan Kehutanan (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT) yaitu seluas 543 ribu hektare.
Tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan dengan wilayah kelola masyarakat menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan. Data FWI pada tahun 2013 sampai 2017, memperlihatkan trend peningkatan jumlah konflik yang signifikan di delapan Provinsi yang menjadi fokus kajian. Dari 161 konflik di tahun 2013, bertambah menjadi 1084 kasus di tahun 2017. konflik yang terjadi didominiasi oleh konflik antara masyarakat dan perusahaan. Dalam hal ini antara masyarakat dengan HPH, HTI, perkebunan, dan pertambangan. Pada rentang waktu 2013-2017, Dari 1084 konflik yang terekam oleh FWI, sekitar 97% atau 1049 kasus terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Sisanya 5 kasus antara perusahaan dengan pemerintah, 7 kasus perusahaan dengan perusahaan, 15 kasus pemerintah dengan masyarakat, dan 8 kasus konflik horizontal antar masyarakat.
Meningkatnya konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat tidak lepas dari semakin bertambahnya luasan hutan dan lahan yang dikelola oleh perusahaan. Peningkatan jumlah konflik yang sangat signifikan ialah konflik yang terjadi di sektor perkebunan. Hal ini juga sejalan dengan semakin maraknya ekspansi perkebunan kelapa sawit saat ini. Pada tahun 2013, di sektor perkebunan hanya terekam 38 kasus konflik di 8 Provinsi. Konflik di sektor perkebunan terus meningkat signifikan hingga di tahun 2017 menjadi 723 kasus.
Peningkatan signifikan jumlah kasus konflik juga terjadi di sektor kehutanan, tepatnya pada sektor Hutan Tanaman Industri (HTI/IUPHHK-HT). Di sektor HTI, pada tahun 2013 terekam 21 kasus dan meningkat menjadi 115 kasus di tahun 2017. Hal berbeda terjadi di sub sektor kehutanan lainnya di HPH (IUPHHK-HA). Penambahan jumlah konflik di area konsesi HPH tidak sesignifikan seperti halnya di perkebunan dan HTI. Hal ini juga sejalan dengan trend pengelolaan sumberdaya hutan yang beralaih dari HPH ke HTI.
Dalam penelitian ini, secara khusus terdapat empat kasus yang diulas oleh FWI untuk melihat dampak yang terjadi akibat tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan. Keempat kasus yang diulas dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan berdampak pada konflik sosial yang berkepanjangan dan hilangnya hutan alam di lokasi tumpang tindih tersebut.
1. Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
| Masyarakat Muara Tae secara turun-temurun sudah menetap di sepanjang aliran sungai nayan, anak sungai Ohokng. Masyarakat Adat Muara Tae dalam melangsungkan kehidupannya sangat tergantung dengan kelestarian sumber daya hutan. Hutan telah menyatu dengan kehidupan mereka baik dari sisi sosial, budaya dan ekonomi. |
| Kehidupan dan kebersahajaan Masyarakat Adat Muara Tae mulai terusik ketika hadirnya perusahaan berbasis lahan. Dimulai sejak 46 tahun yang lalu, dimana kawasan hutan dan wilayah kampung Muara Tae sudah menjadi rebutan berbagai perusahaan HPH, HTI, kebun sawit, hingga pertambangan. Sejak tahun 1971, kekayaan alam kecamatan Jempang termasuk Muara Tae di dalamnya mulai dikeruk dengan beroperasinya perusahaan HPH, PT. Sumber Mas. Pada areal yang sama, PT. Sumber Mas juga membangun HTI diawal 1993. Kemudian tahun 1995, giliran perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. London Sumatra mulai beraktivitas di Muara Tae. Tidak berhenti sampai disitu, sekitar tahun 1996/1997, perusahaan tambang batubara, PT.Gunung Bayan Pratama Coal ikut meramaikan perizinan di wilayah Muara Tae. |
| Kemudian pada tahun 2010, 2011, dan 2012 secara berturut-turut Muara Tae kembali disusupi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Perusahan tersebut adalah PT. Borneo Surya Mining Jaya (Surya Dumai Grup (Keluarga Fangiono)), PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resouces Bhd Grup), dan PT. Gemuruh Karsa. |
| Sudah 46 tahun, Muara Tae terus-menerus kehilangan sebagian besar wilayah dan hutan mereka oleh HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Padahal masyarakat Muara Tae sendiri tidak pernah menyerahkan wilayah adat mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga saat ini, masyarakat Muara Tae masih berusaha bertahan dari gempuran konsesi-konsesi. |
| Kondisi kesilangsengkarutan ini, mendorong terjadinya perubahan tutupan hutan alam di Muara Tae. Catatan FWI pada 2000, Muara Tae masih memiliki hutan alam seluas 854 hektare. Namun situasi hari ini, wilayah adat Muara Tae sudah tidak lagi memiliki hutan alam tersisa. |
2. Desa Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
| Mayoritas masyarakat Muara Lambakan hidup dari berladang dan berkebun. Ditinjau dari aspek kesejarahannya, Masyarakat ini secara turun-temurun sudah menghuni wilayah Sungai Lambakan yang merupakan anak sungai Sub-DAS (Daerah Aliran Sungai) Telake sejak tahun 1830, namun secara definitif Desa Muara Lambakan ini terbentuk semenjak 1970. |
| Masyarakat Muara Lambakan menilai keberadaan hutan sangat berperan untuk mendukung eksistensi adat-istiadatnya, sebab masyarakat Adat Paser di Desa Muara Lambakan meyakini bahwa keberadaan hutan adat di Desa Muara Lambakan harus senantiasa dijaga dan dirawat karena di sana bermukim jejak para leluhur mereka. |
| Namun sejak hadirnya perusahaan berbasis lahan, hak dan akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan dan lahan semakin berkurang. Saat ini, ada lima perusahaan HTI dan HPH yang mengepung desa, PT. Fajar Surya Swadaya, PT. Greaty Sukses Abadi, PT. Balikpapan Forest Ind., PT. Indowana Arga Timber, dan PT. Telagamas Kalimatan. Seluas 31,57 ribu hektare atau 68 persen wilayah desa sudah dibebani izin oleh HTI dan HPH. Sementara jauh lebih sedikit wilayah desa yang bebas izin seluas 15 ribu hektare atau 32 persen. Itupun 10 ribu hektare atau 67 persen wilayah yang bebas izin sudah dicadangkan untuk HPH. |
| Hadirnya perusahaan HPH maupun HTI di Desa Muara Lambakan dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya akses atau bahkan tersingkirnya masyarakat dari tanahnya. Bahkan yang lebih parah, menyebabkan rusaknya ekosistem di daerah tersebut. Catatan FWI dalam rentang 2000-2016, Muara Lambakan telah kehilangan 4,9 ribu hektare hutan alam atau sebelas persen dari luas wilayahnya. |
| Berbagai upaya penolakan terhadap kehadiran perusahaan sudah ditempuh masyarakat. Melakukan hearing ke DPRD Kabupaten, hingga hearing di tingkat DPRD Provinsi Kaltim. Akan tetapi belum ada solusi nyata yang dihasilkan dari upaya tersebut. Sementara Aktivitas pembukaan dan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh PT. Fajar Surya Swadaya di wilayah Desa Lambakan terus berjalan. |
3. Muara Jawa, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
| Muara Jawa adalah nama kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ketentraman hidup masyarakat Muara Jawa mulai terusik semenjak hadirnya PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PKU I) yang mendapat izin perkebunan kelapa sawit dan PT. Kutai Energi (KE) yang mendapat izin tambang batu bara. Kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT. Toba Bara Sejahtera Group yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. |
| Luas konsesi PT. PKU I adalah 11,5 ribu hektare yang meliputi empat kecamatan yaitu, Loa Janan, Muara Jawa, Palaran, dan Sanga-sanga. Sementara luas konsesi PT. KE adalah 6,8 ribu hektare, meliputi tiga kecamatan, Loa Janan, Muara Jawa, dan Sanga-sanga. Analisis FWI 2017 menunjukkan bahwa dilokasi yang sama (Loa Janan, Muara Jawa, dan Sanga-sanga), 4,7 ribu hektare lahan tumpang tindih antara PT. PKU I dengan PT. KE. Artinya, 40 persen wilayah PT. PKU I masuk ke dalam PT. KE, sementara 70 persen wilayah PT. KE masuk ke dalam PT. PKU I. |
| Kemudian hampir 2 ribu hektare wilayah kelola masyarakat tumpang tindih dengan PT. PKU I dan PT. KE. Kehadiran perusahaan tersebut justru menggusur lahan-lahan produktif masyarakat yang selama ini digunakan untuk berladang dan bertani. Lahan masyarakat yang telah digusur tersebut milik enam kelompok tani yang terdiri dari kelompok tani Maju Bersama seluas 845,4 hektare, Untung Tuah Bersama 89,31 hektare, Gotong royong 230 hektare, Berkah Mulia 23 hektare, Mandiri 410,1 hektare, dan Sungai Mukun 196,2 hektare. Dari lahan tersebut, beberapa sudah memiliki legalitas SHM dan SPPT sejak 1987 dan 1997. |
| Puncak perlawanan masyarakat terjadi pada tahun 2016. Masyarakat memutuskan melakukan perlawanan dengan memagar tanahnya, membuat pondok-pondok kembali, dan melakukan ternak sapi sebagai simbol perlawanan ekonomi tanding terhadap PT PKU I. Selain itu, keenam Kelompok Tani kembali melaporkan kasus pidana kepada Mabes Polri atas dugaan perampasan tanah dan penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh PT PKU I. |
4. Kemukiman Manggamat, Aceh Selatan, Aceh
| Di sepanjang 13 kabupaten Provinsi Aceh dan 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terbentang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 2,6 juta hektare. Sebuah kawasan khusus yang pada 1998 ditetapkan sebagai kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam. Kini, KEL juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Kawasan strategis nasional berarti wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. |
| Kemukiman Manggamat, merupakan wilayah komunitas masyarakat adat Manggamat, yang termasuk di dalam Kabupaten Aceh Selatan. Terdiri dari 13 gampong (desa), Kemukiman Manggamat memiliki wilayah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. |
| Manggamat masih menyimpan tutupan hutan alam seluas 110,9 ribu hektare, lebih dari 90% luas wilayah adat Manggamat. Hidup berdampingan dengan hutan membuat masyarakat di Manggamat memiliki ketergantungan dan interaksi yang tinggi dengan hutan di sekitar pemukiman mereka. Interaksi dengan hutan tidak hanya sebatas mengambil manfaat dari hutan, tapi sebagai komunitas masyarakat adat, masyarakat di Manggamat memiliki aturan dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan merusak hutan. |
| Di sisi lain, kebijakan Bupati yang didukung oleh Gubernur memberikan izin-izin perusahaan tambang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, beroperasi di dalam wilayah Kemukiman Manggamat. Dalam rentang 2010-2012, di Kemukiman Manggamat, ada tujuh izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur. Di antaranya adalah pertambangan emas dan bijih besi. Padahal Kemukiman Manggamat yang terdiri dari 13 desa terletak di hulu Sungai Kruet, dan dikelilingi pegunungan yang masuk dalam wilayah KEL. Tujuh perusahaan tambang yang diberikan izin beroperasi di Manggamat adalah PT Multi Mineral Utama, PT Beri Mineral Utama, PT Aneka Mining Nasional, PT Arus Tirta Power, PT Bintang Agung Mining, PT Aspirasi Widya Chandra, dan KSU Tiega Manggis. |
| Sejumlah perusahaan tersebut konsesinya telah merebut wilayah adat Kemukiman Manggamat hingga seluas 10,7 ribu hektare. Artinya 54 persen dari wilayah adat Kemukiman Manggamat telah menjadi konsesi tambang. Sementara total luas tujuh konsesi pertambangan tersebut mencapai 37,1 ribu hektare. |
| Di Kemukiman Manggamat, keberadaan empat perusahaan tersebut dan akibat dari beroperasinya tiga perusahaan sebelumnya, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Selama 2016, beberapa kali banjir besar melanda Kemukiman Manggamat. Juli 2016, banjir besar menyapu kebun palawija warga, namun hingga kini kerugian yang diderita masyarakat tidak dihitung. Pada September dan November 2016, banjir besar melanda kembali. |
| Sejak hadirnya perusahaan tambang di 2010, dari 2009 hingga 2016, hutan alam di kawasan tersebut telah hilang seluas 1,5 ribu hektare (FWI, 2017). Dimana 810 hektare tutupan hutan alam yang hilang, berada di dalam wilayah tambang. |
| Analisis FWI 2017, hutan di KEL sendiri dalam kurun waktu 2009-2016, berkurang hingga 107,6 ribu hektare. Pengurangan luas hutan tersebut wajar, bila melihat banyaknya konsesi tambang di dalam KEL. Luas deforestasi di wilayah tersebut memang tidak luas, bila dibandingkan dengan luas wilayah adat Manggamat maupun luas KEL. Namun dampak dari deforestasi tersebut justru besar dan nyata, yaitu berupa bencana banjir dan longsor yang terus menerus dialami warga. |
Beberapa contoh kasus diatas memperlihatkan bahwa tumpang tindih penggunaan lahan berdampak pada hilangnya hutan alam maupun menyebabkan konflik tenurial. Kasus tumpang tindih penggunaan lahan di Muara Tae antara masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit dan tambang, tidak menyisakan hutan alam bahkan menciptakan konflik berkepanjangan. Konflik yang awalnya hanya melibatkan dua aktor antara masyarakat dan perusaahan, kini berkembang menjadi konflik horizontal yang melibatkan perselisihan antar masyarakat adat. Begitu juga tumpang tindih penggunaan lahan di Muara Lambakan yang melibatkan masyarakat adat dengan HPH dan HTI, menghilangkan 4,9 ribu hektare hutan alam dalam rentang 2000-2016 dan menimbulkan konflik. Penyelesaian konflik yang belum menjawab permasalahan dasar (akses kelola masyarakat) justru berpotensi memperbesar konflik di Muara Lambakan.
Hal serupa juga terjadi di Muara Jawa. Tumpang tindih penggunaan lahan antara masyarakat dengan tambang dan sawit, menghilangkan hutan alam tersisa di Muara Jawa seluas 166 hektare dan menimbulkan drama konflik. Kehadiran perusahaan yang justru menggusur lahan-lahan produktif masyarakat yang selama ini digunakan untuk berladang dan bertani, justru akan semakin menyengsarakan masyarakat. Pun juga kasus tumpang tindih antara masyarakat adat Manggamat dengan tambang, menghilangkan 1,5 ribu hektare hutan alam pada rentang 2009-2016 dan menciptakan konflik. Wilayah Manggamat yang masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang seharusnya dijaga, malah menjadi obyek eksploitasi.
Apabila memperhatikan kasus-kasus diatas, nyata bahwa wilayah dengan luas hutan alam besar, berpotensi kehilangan hutan/deforestasi yang juga besar. Kasus di Muara Lambakan dan Manggamat, wilayah yang berada di kawasan hutan lebih kuat dari sisi deforestasi. Karena hutan alam yang tersisa lebih luas bila dibandingkan dengan Muara Tae dan Muara Jawa yang wilayahnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
Dengan demikian, nyata bahwa benang merah dari kasus tumpang tindih penggunaan lahan ini, utamanya adalah: (1) permasalahan tumpang tindih berdampak pada hilangnya hutan alam. Tentu saja beberapa kasus yang ditampilkan hanyalah sebagian dari banyak contoh lain di nusantara ini yang dengan modus sejenis yang terkait dengan silang-sengkarut/tumpang tindih lahan menjadi penyebab dari deforestasi; (2) Konflik agraria struktural. Semua kasus dalam studi ini menunjukkan bahwa dampak langsung dari tumpang tindih sengkarut pengelolaan hutan dan lahan adalah konflik berbasis tanah dan SDA. Baik yang bersifat vertikal, horizontal maupun kombinasi keduanya; (3) Dampak-dampak lanjutan lainnya. Di antara dampak lanjutan dari deforestasi dan konflik akibat dari tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan tersebut adalah beragam krisis sosial-ekologis pedesaan, kriminalisasi, kekerasan, pelanggaran HAM, marjinalisasi, dan pengusiran paksa msyarakat dari ruang hidupnya sendiri.
Sementara benang merah aktor utama penyebab tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan ini adalah (1) rezim perusahaan HTI; (2) pemegang ijin HPH; (3) perkebunan sawit, dan (4) rezim pertambangan. Rezim pemilik lahan skala luas ini memiliki ragam dan variasinya sendiri-sendiri dalam memuluskan land grabbing mereka. Namun demikian, benang merahnya sama, mengabaikan daya dukung sumberdaya hutan dan keberlanjutannya. Corak dan wataknya selaras dengan analisa Prof. Hariadi Kartodihardjo, legal non legitimed. Memenuhi prosedur formal “legal” administratif, namun absen legitimasi dan menjauhi dimensi keadilan sosial-ekologis.